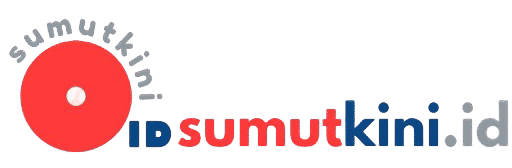Usia ke-79 bagi sebuah organisasi bukan sekadar penanda lamanya waktu, melainkan cermin perjalanan nilai, konsistensi perjuangan, dan arah masa depan. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yang lahir dari kegelisahan intelektual dan tanggung jawab kebangsaan pada 5 Februari 1947, kini berada pada fase penting sejarahnya.
Pertanyaannya tidak lagi sederhana: masih adakah peran HMI bagi demokrasi Indonesia? Melainkan lebih mendalam: bagaimana HMI memilih perannya di tengah perubahan zaman dan bertanggung jawab merawat demokrasi Indonesia? Sejak awal kelahirannya, HMI memposisikan diri sebagai organisasi mahasiswa yang memadukan nilai keislaman dan keindonesiaan.
Dua nilai ini bukan slogan historis, tetapi fondasi etik yang menuntut keberpihakan pada keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial. Dalam bingkai tersebut, demokrasi bukan hanya sistem politik, melainkan arena perjuangan nilai. HMI hadir bukan untuk sekadar meramaikan sejarah, melainkan untuk ikut mengoreksi arah bangsa.
Dalam lintasan sejarah nasional, HMI telah menunjukkan kontribusi yang tidak kecil. Kader-kadernya pernah berdiri di barisan kritik terhadap kekuasaan yang otoriter, memperjuangkan kebebasan berpendapat, dan menyuarakan kepentingan rakyat.
Namun, sejarah bukan warisan yang otomatis menjamin relevansi. Ia justru menghadirkan beban moral bagi generasi penerus: apakah semangat kritis itu masih hidup, atau hanya dikenang sebagai romantisme masa lalu? Begitu juga keterlibatan Alumni kader-kader HMI dalam berbagai fase politik nasional menunjukkan dinamika relasi antara organisasi mahasiswa dan kekuasaan.
Di satu sisi, HMI kerap tampil sebagai kekuatan kritis terhadap kebijakan negara yang dinilai menyimpang dari prinsip keadilan dan demokrasi. Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian Alumni kader HMI memasuki ruang-ruang politik praktis dan birokrasi negara. Kondisi ini menghadirkan tantangan internal, terutama terkait dengan konsistensi nilai dan independensi organisasi.
Demokrasi Indonesia hari ini menghadapi tantangan yang subtil tetapi mendalam. Ia tidak runtuh oleh kudeta atau pembubaran konstitusi, melainkan mengalami erosi perlahan melalui pragmatisme politik, oligarkisasi kekuasaan, pelemahan etika publik, dan menyempitnya ruang kritik. Dalam kondisi seperti ini, peran HMI tidak dituntut untuk selalu menjadi oposisi, tetapi dituntut untuk selalu berpihak pada kebenaran karena demokrasi membutuhkan suara-suara jujur yang lahir dari nalar sehat dan keberanian moral.
Dalam konteks ini, HMI memiliki modal besar: tradisi intelektual, jaringan kader, dan legitimasi sejarah. Modal ini akan bermakna jika digunakan untuk memperjuangkan menegakkan nilai-nilai demokrasi, sehingga tidak jarang alumni kader-kader HMI yang focus dan mengabdikan dirinya di Lembaga-lembaga penggiat pemilu dan penyelenggara pemilu sehingga demokrasi dapat terjaga baik dari dalam maupun dari luar.
Di usia ke-79, HMI berada pada persimpangan: antara tetap menjadi moral force dan intellectual force, atau bertransformasi menjadi organisasi yang larut dalam rutinitas struktural dan kepentingan jangka pendek. Keterlibatan kader HMI di ruang-ruang kekuasaan sejatinya bukan persoalan, selama tetap menjaga jarak kritis dan kesetiaan pada nilai.
Yang menjadi persoalan adalah ketika kekuasaan justru mendikte arah berpikir dan sikap organisasi.Milad ke-79 seharusnya menjadi momentum refleksi kolektif. Apakah proses kaderisasi masih melahirkan insan akademis yang kritis dan berintegritas? Apakah forum-forum intelektual masih menjadi ruang dialektika, atau sekadar formalitas agenda? Dan yang lebih penting, apakah HMI masih berani bersuara ketika demokrasi kehilangan substansinya? Usia ke-79 bukan sekadar angka kebanggaan, melainkan penanda kedewasaan organisasi.
Kedewasaan menuntut keberanian untuk mengkritik diri sendiri, memperbarui orientasi gerakan, dan meneguhkan kembali Nilai Dasar Perjuangan sebagai kompas etik. Tanpa refleksi semacam itu, usia panjang justru dapat menjelma menjadi beban, bukan kekuatan.
Pada akhirnya, masa depan demokrasi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh elit politik, tetapi juga oleh keteguhan masyarakat sipil, termasuk organisasi mahasiswa. HMI, di usianya yang ke-79, masih memiliki peluang besar untuk tetap relevan dan bermakna. Namun peluang itu hanya dapat diwujudkan jika HMI memilih untuk tetap setia pada nilai, bukan larut dalam kenyamanan.
Dengan demikian, Milad bukan hanya perayaan usia, tetapi peringatan tanggung jawab, mampu menjaga demokrasi jika—dan hanya jika—ia memilih untuk tetap berpihak pada nilai, bukan pada kenyamanan kekuasaan.
Usia ke-79 bukan sekadar angka historis, melainkan titik evaluasi: apakah HMI masih ingin menjadi penjaga demokrasi, atau sekadar penonton yang hadir di pinggir sejarah.
Rido Hamdani Lubis, S.Sos.I., M.Sos.
Penulis adalah Mantan Aktifis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), saat ini menjabat sebagai Komisioner KPU Labuhanbatu Selatan.